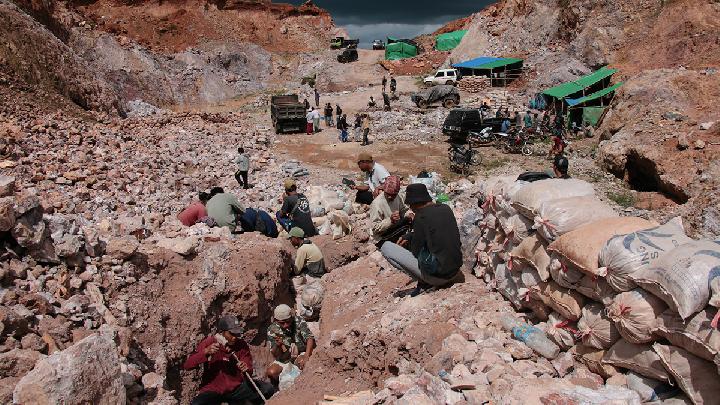Oleh : Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan Penasihat Institute for Democracy Education (ISMES)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini kekuatan neokonservatif AS di bawah Presiden Donald Trump dan pemerintahan sayap kanan rasis Israel pimpinan PM Benjamin Netanyahu sedang mencoba menulis ulang Timur Tengah di mana Israel adalah hegemon yang mengendalikan kawasan vital itu sebagai proksi AS. Ini pekerjaan yang tidak mudah – dan kontraproduktif – di tengah resistensi seluruh negara di kawasan.
Timteng baru adalah kawasan tanpa rezim mullah Iran, tanpa negara berdaulat Palestina, dan tanpa Hamas, Hizbullah, Houthi, dan Kataib Hizbullah di Irak. Untuk itu Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pimpinan Trump diluncurkan dan pengerahan aset militer AS skala besar di sekitar Iran untuk memaksakan pergantian rezim di sana.
Tapi Teheran juga telah mengokang senjata siap untuk membalas seketika serangan AS. Sementara ruang diplomasi sangat sempit. AS mengajukan syarat-syarat penghindaran perang yang mustahil bisa dipenuhi Iran. Syarat-syarat itu adalah Iran menghentikan secara total program nuklir dan rudalnya serta menghentikan dukungan pada proksi-proksinya di Kawasan.
Trump masih buying time menunggu Iran menyerah karena dampak perang tak dapat diprediksi dan sulit dikontrol. Sangat mungkin serangan AS kali ini hanya ditujukan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan tokoh-tokoh pentingnya untuk memungkinkan pergantian rezim Tapi skenario ini ceroboh dan superfisial.
BoP bertujuan menguburkan cita-cita Palestina memiliki negara. Dus, BoP dan regime change di Iran merupakan proyek Zionis untuk mewujudkan Israel Raya. Kekhawatiran inilah yang mendorong Turki, Arab Saudi, Oman, dan Qatar, melakukan deeskalasi. Perang akan mendestabilisasi kawasan yang bertentangan dengan visi masa depan mereka.
Upaya meruntuhkan rezim mullah telah dilakukan para presiden AS sejak berdirinya Republik Islam pada 1979 melalui revolusi yang meruntuhkan Dinasti Pahlevi, sekutu strategis AS dan Israel. Setelah peluncuran BoP yang kontroversial, tetapi didukung kubu Arab-Islam, Netanyahu juga melihat konsep Strategi Keamanan Nasional AS sejalan dengan proyek Zionisme.
BoP, yang dikendalikan Trump secara mutlak, tidak menyebut Gaza dan tidak menyertai Palestina dalam pengambilan keputusan. Memang BoP disebut berbasis pada Resolusi DK PBB 2803. Tetapi Cina dan sekutu penting AS di Eropa – seperti Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol – menolak bergabung karena BoP tidak sesuai dengan semangat resolusi DK PBB 2803.
BoP mestinya bersifat inklusif dengan menyertakan semua anggota PBB. Faktanya, lembaga ini dipimpin Trump, menantunya Jared Kushner, dan kroni-kroninya. Tugas BoP adalah rekonstruksi Gaza dengan terlebih dahulu melucuti pejuang bersenjata Palestina di sana. Karena itu, BoP memiliki instrumen militer, Pasukan Stabilisasi Internasional, pimpinan AS untuk melakukan tugas ini
Sementara itu, rezim mullah harus dibubarkan karena dia satu-satunya kekuatan di Timteng yang independen, strategis secara geografis, dan kaya energi. Ini dilihat sebagai ancaman eksistensial Israel. Sama sebagaimana Iran, berdirinya negara Palestina dipandang akan menguburkan aspirasi biblikal Israel untuk mewujudkan Israel Raya dan mengancam eksistensinya di masa depan.
Dus, dua hal ini harus dicegah berapa pun ongkosnya. Tapi Israel tak mampu melakukannya sendirian. Pada Juni tahun lalu, Israel mengerahkan 200 jet tempur dalam menyerang Iran. Belakangan AS ikut membantu mengebom situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Puluhan petinggi militer dan pakar nuklir Iran tewas. Tapi misi itu gagal mencapai tujuannya.
Dengan kapasitas militer yang digdaya disertai impunitas yang diberikan AS dan sekutu Barat, Israel juga gagal menundukkan Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Di Suriah, Israel melancarkan serangan ke seluruh situs-situs militer pasca keruntuhan rezim Bashar al-Assad. Upaya melemahkan pemerintahan baru di bawah Presiden Interim Ahmad al-Sharaa dengan mendorong pemberontakan Druze dan Kurdi juga tak membuahkan hasil.
Upaya melucuti Hizbullah di Lebanon juga gagal. Kendati gencatan senjata Hizbullah-Israel yang dimediasi AS telah dicapai pada November 2024, Israel tak mematuhi syarat gencatan senjata yang mengharuskannya mundur dari tertitori Lebanon. Dan AS mendiamkannya. Bahkan, sampai kini Israel masih menyerang Lebanon selatan yang menyerupai ethnic cleansing. Kalau pemerintahan Presiden Joseph Aoun memaksakan diri melucuti Hezbollah sesuai janjinya pada AS, maka potensi perang saudara di sana tak terelakkan.
Perkembangan di Yaman pun tidak menggembirakan Israel. Sekonyong-konyong kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) dukungan UEA melakukan ekspansi ke timur, yang memicu konflik UEA dengan Arab Saudi yang mendukung Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) yang legitimasinya diakui PBB. Konflik STC-PLC yang tadinya berada dalam satu kubu menguntungkan Houthi.
Proyek Zionisme membangun Israel Raya menemukan momentum ketika Trump kembali ke Gedung Putih. Dalam konsep Strategi Keamanan AS yang dirilis tahun lalu, pemerintahan Trump memprioritas hegemoninya di western hemisphere (belahan barat) sesuai Monroe Doctrine yang mengamanatkan AS menjadikan Amerika Latin bebas dari pengaruh kekuatan luar kawasan.
Maka, kita menyaksikan AS menyerang Venezuela, menculik Presiden Nicolas Maduro, dan mengancam Kuba. Keduanya merupakan sahabat Cina, Rusia, dan Iran. Trump juga mengancam akan merampas Greenland milik Denmark yang, sebagaimana Venezuela dan Iran, menyimpan minyak dan mineral tanah jarang yang strategis.
Dalam Strategi Keamanan Nasional-nya, pemerintahan Trump tak lagi menjadikan Timteng sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Untuk itu, Israel bisa menjaga keamanannya sendiri sehingga AS bisa mengurangi kehadiran militernya di kawasan itu, yang berbiaya tinggi. Dengan sendirinya, Iran sebagai ancaman harus dilenyapkan dan isu Palestina dihilangkan untuk memungkinkan integrasi Israel ke dalam Timteng melalui Abraham Accord (Perjanjian Ibrahim).
Setelah perang 12 hari pada Juni gagal mencapai tujuan, momentum muncul kembali menyusul kaum pedagang di Teheran memprotes kejatuhan mata uang rial, melejitnya inflasi, dan mencekik kehidupan rakyat. Protes itu menjalar cepat ke kota-kota Iran dan isunya berubah dari isu ekonomi menjadi isu politik. Agen-agen Israel dan AS di sana mengorkestrasi pemberontakan.
Amblasnya ekonomi Iran tak bisa dilepaskan dari sanksi AS dan sekutu Barat setelah berdirinya Republik Islam pada 1979 melalui revolusi pimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini. Revolusi itu menghancurkan Nixon Doctrine yang membangun Poros Israel-Iran untuk mengimbangi Arab. Runtuhnya Monarki Pahlevi membuat konstelasi politik Timteng berubah.
Israel menjadi rentan setelah perang 1973 menghadapi Mesir dan Suriah tak lagi menghasilkan kemenangan. Maka, perdamaian dengan Mesir, tulang punggung militer Arab, pada 1979 bukan lagi opsi, melainkan esensial. Israel rela melepaskan seluruh Sinai milik Mesir yang dicaplok Israel pada 1967. Tapi hal itu tak mengurangi kerentanan Israel menghadapi Iran.
Setelah diembargo AS dan Barat, Iran juga harus berperang dengan Irak di bawah Presiden Saddam Hussein selama delapan tahun (1980-1988). Perang menguras lebih jauh sumber daya ekonomi Iran. Munculnya ISIS yang menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah pada 2014 membuat AS butuh bantuan Iran untuk menghancurkannya. Maka, pada 2015 AS ikut menandatangani kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).
JCPOA mengharuskan Iran membatasi pengayaan uraniumnya hanya pada aras 3,67 persen yang sejalan dengan Pakta Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Pengawas nuklir PBB (IAEA) diberi wewenang mengawasi program nuklir Iran secara ketat. Sebagai imbalan, Iran bebas mengekspor minyaknya ke pasar global. Selama tiga tahun kesepakatan ini berjalan dengan memuaskan sampai AS pimpinan Trump mundur secara sepihak pada 2018.
Mundurnya Trump pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021) itu tak bisa dilepaskan dari pandangannya mengenai Strategi Keamanan Nasional AS dan rayuan Netanyahu. Tak kurang penting, negara-negara Arab Teluk pun tak puasa dengan kesepakatan itu karena tidak mencakup keharusan Iran menghentikan program rudal balistiknya dan tak lagi mencampuri urusan domestik di Irak, Lebanon, dan Yaman.
Sama sebagaimana keprihatinan Arab Teluk, Netanyahu dan Trump juga melihat keleluasaan Iran mengekspor minyaknya dan melanjutkan program rudal balistik serta politik ekspansifnya membuat Iran terlihat sebagai ancaman nyata bagi kepentingan mereka. Kendati Trump telah mundur dari JCPOA, Iran masih patuh pada kesepakatan itu karena penandatangan lain – Rusia, Cina, Perancis, Inggris, dan Jerman -- tetap berkomitmen.
Bagaimanapun, segera setelah AS mundur, inflasi di Iran langsung melejit yang memicu demonstrasi di mana-mana. Tetapi Teheran bisa mengatasinya karena masih punya anggaran untuk meningkatkan subsidi bahan pokok pada masyarakat kelas bawah. Pada demonstrasi kali ini, yang pecah pada 28 Desember, situasi menjadi sangat sulit bagi rezim karena kondisi-kondisi berikut.
Pertama, Iran tak punya lagi ruang fiskal untuk mengatasinya. Hal ini terakumulasi dengan ketidakpuasan rakyat atas maraknya korupsi, salah urusan pemerintahan, dan tindakan represif terhadap kebebasan. Padahal, luka sosial belum sembuh pasca kebijakan keras pemerintah atas demonstrasi besar yang melanda kota-kota Iran selama berbulan-bulan pada 2022-2023 menyusul kematian Mahsa Amini di tahanan kepolisian karena melanggar kode berbusana.
Kedua, kendati menjadi Wapres AS pada era Barack Obama, Presiden Joe Biden malah menambah sanksi baru karena Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen. Pecahnya perang Rusia-Ukraina (2022) di mana drone Iran dipakai Rusia dan pecahnya perang Hamas-Israel (2023) di mana Hizbullah dan Houthi ikut mengeroyok Israel membuat perundingan Iran-AS untuk memulihkan JCPOA sulit dicapai.
Ketiga, setelah perang Juni yang melemahkan kapasitas militer Iran, runtuhnya rezim Bashar al-Assad yang disokong militer Iran, serta berantakannya poros perlawanan setelah Hezbollah dilemahkan, strategi dan kemampuan rezim mullah menjaga teritori Iran dipertanyakan. Terutama setelah Mossad berhasil membobol intelijen Hizbullah yang berujung pada pembunuhan para pemimpinnya, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, dan perang Juni.
Keempat, pada September, Inggris, Perancis, dan Jerman menginisiasi pemberlakuan kembali secara otomatis seluruh sanksi PBB terkait pembatasan Iran terhadap kerja samanya dengan IAEA. Hal ini memperparah kondisi ekonomi Iran, yang memicu demonstrasi mematikan. Dalam menghadapi tekanan internal dan eksternal yang mengancam eksistensi rezim, tak ada pilihan lain kecuali bertindak keras. Teheran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas, termasuk 100-an aparat. Sumber Human Right Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS mengungkapkan, yang tewas mendekati 10 ribu orang.
Trump menjadikan kekerasan berdarah di Iran sebagai justifikasi untuk penggantian rezim. Pada saat sama, Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada belasan pejabat dan entitas Iran, serta menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris. Kendati kita kecewa pada kematian begitu banyak demonstran Iran, sikap AS dan UE tersebut mengungkapkan secara telanjang watak munafik mereka alias standar ganda.
Bagaimana mungkin watak munafik bisa disembunyikan ketika mereka membiarkan genosida dan ethnic cleansing Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon? Toh, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas tuduhan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.
Sikap UE bermotif politik. Ia ingin membantu AS meningkatkan pressure atas Iran. Juga untuk meneguhkan konsistensinya menentang kekerasan Rusia di Ukraina. Dengan begitu, diharapkan Trump bisa mempertimbangkan ulang sikapnya yang moderat terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan bersedia memberikan konsesi teritori Ukraina terhadap Rusia guna mengakhiri perang.
Dus, tidak ada moralitas, hukum, atau norma apapun yang mendikte kebijakan negara kecuali kepentingan nasionalnya. Tapi konsekuensinya justru negatif. Bagaimana mungkin UE hendak mempertahankan tatanan lama berbasis hukum yang hendak dihancurkan Trump bila mereka inkonsisten dalam menjaga kemanusiaan universal dan patuh pada semua konvensi PBB yang sedang dilanggar Israel secara telanjang?
Trump menyatakan ia hendak membangun “peace through strength.” Prinsip inilah yang sedang diperlihatkan pada upaya menyelesaikan isu Palestina dan Iran dengan bekerja sama dengan Netanyahu. Apakah menulis ulang Timteng keduanya akan berbuah hasil? Saya sangat skeptis. BoP yang kontroversial itu sendiri tak akan mudah direalisasikan.
Negara-negara Arab dan Islam yang mendukungnya akan menghadapi resistensi publiknya sendiri karena keikutsertaan mereka mudah dipersepsikan sebagai kolaborasi dengan kekuatan kolonialis-imperialis. Toh, Netanyahu diterima sebagai anggota BoP, sementara wakil Palestina tidak. Israel juga tak bersedia melepaskan kendalinya atas Gaza dan Tepi Barat untuk memastikan negara Palestina tidak akan terwujud.
Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin AS untuk demiliterisasi Gaza dan melucuti Hamas akan kontraproduktif bagi keamanan domestik negara Arab dan Islam. Itu sebabnya, berbeda dengan Indonesia, negara-negara Arab tak bersedia menyumbangkan tentara ke pasukan yang bakal berlaku keras terhadap pejuang Palestina tetapi toleran bagi agenda Israel.
Resistensi negara Arab, Turki, Pakistan, India, Cina, dan Rusia terhadap niat Trump menyerang Iran memperlihatkan kekhawatiran pada dominasi Israel di kawasan. Di luar kekhawatiran mereka akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perang Iran versus AS-Israel, pergantian rezim di Iran untuk digantikan rezim pro-Israel dan pro-AS akan menciptakan situasi rentan bagi Arab.
Dus, upaya Trump-Netanyahu menggambar ulang Timteng menghadapi tantangan gigantik dan sangat serius. Di dalam negeri mereka sendiri, kebijakan yang memprioritas kekuatan fisik sebagai instrumen utama untuk mengubah perilaku lawan telah meretakkan tatanan sosial-politik di sana. Bahkan, legitimasi keduanya mengalami erosi.
Tangsel, 31 Januari 2026

 2 hours ago
1
2 hours ago
1