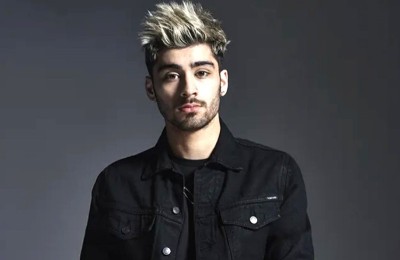REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mas'ud, S. Ag, M.I.Kom*
Beberapa hari terakhir ini, industri penyiaran Indonesia telah memetik pelajaran berharga tentang kedalaman kearifan lokal dan kepekaan dalam menyentuh lembaga keagamaan. Tayangan program Xpose Uncensored, yang disiarkan media televisi Trans7, telah memantik gelombang protes yang tidak hanya memengaruhi dunia media tetapi juga bakal berimbas pada berbagai lini bisnis CT Corp.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan dalam konstruksi realitas media. Teori framing yang dikembangkan oleh Robert Entman (1993) menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi publik dengan menyeleksi dan menyorot aspek-aspek tertentu dari realitas. Sayangnya, dalam program ini, framing yang dibangun malah mengabaikan kompleksitas dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.
Dunia pesantren, yang telah lama menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa, tiba-tiba disajikan secara timpang. Citra yang tidak representatif, narasi yang provokatif, dan penyajian yang tidak sesuai konteks telah melukai perasaan jutaan umat Islam yang memercayai dan meyakini eksistensi dan kontribusi akbar lembaga pesantren.
Media seharusnya menjadi jembatan pemahaman, bukan alat pemecah belah. Dalam budaya pesantren, kiai bukan sekadar tokoh agama, melainkan juga penjaga tradisi keilmuan dan moral bangsa. Menghormati kiai sama saja dengan menghormati mata rantai ( sanad ) ilmu pengetahuan yang telah membentuk peradaban nusantara.
Teori resepsi ( reception) Stuart Hall (1980) membantu kita memahami mengapa komunitas pesantren bereaksi begitu kuat. Mereka bukanlah penerima pasif yang begitu saja menerima setiap konten media. Sebaliknya, mereka terlibat dalam pembacaan oposisional terhadap siaran tersebut, menolak narasi yang dibangun dan melawannya dengan narasi alternatif yang lebih selaras dengan realitas hidup mereka.
Krisis komunikasi yang dialami Trans7 menunjukkan kegagalan penerapan Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs (1995). Alih-alih memberikan respons yang tepat dan tulus, stasiun televisi tersebut justru tampak setengah hati dalam meminta maaf, yang memicu gelombang protes menjadi semakin meluas.
Dalam ekosistem digital saat ini, reputasi merupakan aset berharga. Gerakan boikot yang diperkirakan bakal menyebar di berbagai lini bisnis CT Corp membuktikan teori masyarakat jaringan ( Network Society) dari Manuel Castells (2000), di mana informasi dan pengaruh dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan sosial yang terhubung.
Data dari Nielsen Indonesia menunjukkan bahwa televisi terestrial memang mengalami penurunan jumlah pemirsa yang signifikan. Namun, hal ini jangan dijadikan alasan untuk memproduksi konten yang mengabaikan etika dan kepekaan budaya. Dalam situasi sulit, integritas dan tanggung jawab sosial justeru harus dijunjung tinggi.
Pelajaran penting yang dapat dipetik dari kasus ini adalah bahwa literasi budaya bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap praktisi media. Memahami nuansa budaya, menghormati nilai-nilai agama, dan memiliki kepekaan sosial seharusnya menjadi kompetensi fundamental bagi setiap produsen konten.
Kode etik jurnalistik seharusnya menjadi pedoman utama dalam memproduksi semua konten. Prinsip-prinsip dasar seperti akurasi, keadilan, dan penghormatan terhadap privasi harus dijunjung tinggi, terutama ketika menyangkut lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi panutan bagi masyarakat.
Fenomena ini juga mengingatkan kita pada teori spiral keheningan ( Spiral of Silence Theory) karya Elisabeth Noelle-Neumann (1974). Suara-suara yang mungkin kritis terhadap praktik media merasa memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat mereka, sehingga menciptakan gelombang protes yang malah semakin besar.
Bagi dunia pesantren, kasus ini menghadirkan peluang untuk keterbukaan yang lebih besar. Pesantren dapat lebih proaktif dalam membangun narasi positif tentang diri mereka sendiri. Media sosial dan platform digital menjadi fardhu ‘ain untuk dioptimasi dalam menampilkan wajah pesantren yang sebenarnya sebagai pusat pendidikan yang moderat, adiluhung dan bijaksana.
Sebagai penutup, kita perlu merenungkan nasihat bijak almagfurlah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai ini, bukan alat untuk melemahkannya.
Masa depan industri media Indonesia terletak pada kemampuannya menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, antara mengejar keuntungan dan menjaga martabat bangsa. Kasus Xpose Uncensored seharusnya menjadi titik awal untuk membangun praktik jurnalistik yang lebih beradab dan menghargai keberagaman Indonesia.
Menjelang Hari Santri Nasional tahun 2025 ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara media dan pesantren. Media perlu terbuka untuk belajar dari kearifan pesantren, sementara pesantren perlu terus beradaptasi dengan perubahan zaman sebagaimana prinsip ( Al-Muhāfaẓatu 'alā al-qadīmi ash-ṣāliḥi wa al-akhdzu bi al-jadīdi al-aṣlaḥi). Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Tabik.
*Pemerhati Media, Mantan Jurnalis Televisi, dan Alumnus Pondok Pesantren Tebuireng

 1 month ago
19
1 month ago
19