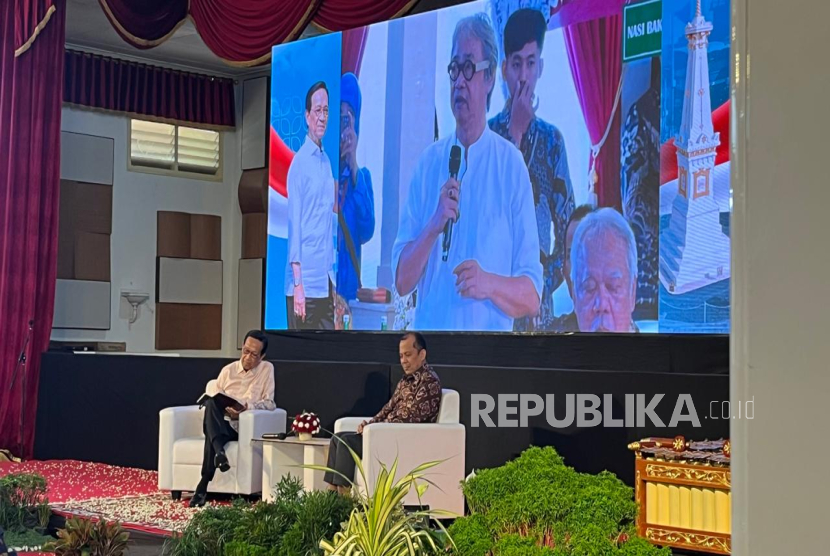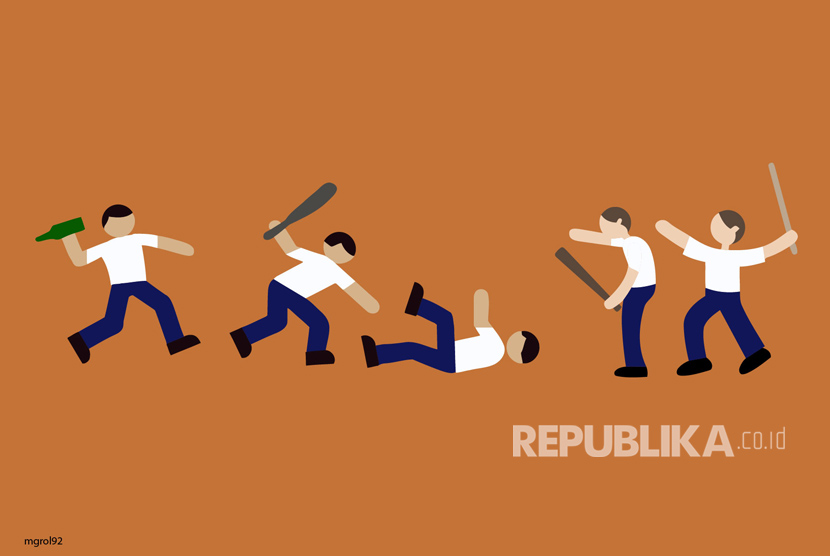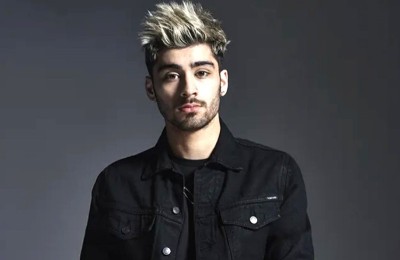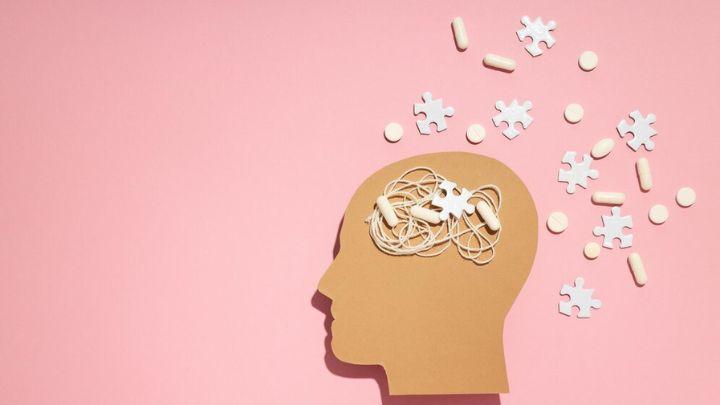Oleh: Hamka Hendra Noer, Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, Sembilan puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan, bangsa ini kembali bertanya: masihkah api itu menyala di dada generasi muda Indonesia? Sumpah Pemuda bukan sekadar momen historis, tetapi pernyataan politik tentang kesatuan, keberanian, dan tanggung jawab moral generasi muda dalam menentukan arah bangsa.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Kini, di tengah pragmatisme dan oligarki elektoral, semangat itu tampak melemah. BPS (2024) mencatat bahwa kelompok usia 16-30 tahun mencapai 24,2% dari total penduduk, sementara mereka yang berusia di bawah 40 tahun mencakup lebih dari separuh pemilih nasional. Namun, CSIS Political Index (2023) menunjukkan bahwa hanya 12% anggota DPR berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun.
Kesenjangan antara potensi demografis dan representasi politik ini mencerminkan defisit regenerasi. Bahkan LSI (2023) menemukan bahwa hanya 34% generasi muda yang percaya kepada partai politik, jauh di bawah kepercayaan terhadap komunitas sosial digital (68%). Dalam istilah Fukuyama (2014), inilah gejala political decay—ketika institusi gagal menyesuaikan diri dengan dinamika sosial generasi baru.
Regenerasi politik yang tersumbat
Masalah kepemimpinan muda tidak terletak pada kurangnya kompetensi, tetapi pada struktur yang tidak membuka ruang regenerasi sejati. Partai politik masih menjadi arena patronase, bukan meritokrasi.
Riset Mietzner dan Aspinall (2024) menunjukkan lebih dari 70% kader muda potensial gagal menembus posisi strategis akibat dominasi elite senior. Fenomena ini sejalan dengan Iron Law of Oligarchy (Michels, 1911)—bahwa setiap organisasi yang mapan cenderung dikuasai oleh sedikit elite yang mempertahankan kekuasaan.
Secara kuantitatif, CSIS (2023) menemukan bahwa hanya 18% partai politik yang memiliki program kaderisasi aktif bagi anggota di bawah 35 tahun. Sementara itu, proporsi caleg muda yang berhasil lolos ke DPR menurun dari 13% (2019) menjadi 10,8% (2024).
Namun, secara kualitatif, banyak aktivis muda menilai partai menjadikan mereka sekadar wajah kampanye. Seorang aktivis dalam studi LIPI (2024) mengatakan, “Kami diberi ruang tampil, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.” Politik akhirnya menjadi panggung yang mempercantik citra, bukan wadah yang menumbuhkan ide.
Padahal, sebagaimana ditegaskan Burns (1978), kepemimpinan transformasional dibangun dari moral purpose—kemampuan membangkitkan kesadaran publik dan memperjuangkan nilai, bukan hanya mengelola kekuasaan. Politik yang kehilangan nilai, lambat laun akan kehilangan legitimasi.
Fenomena ini tidak hanya khas Indonesia, tetapi juga dialami di sebagian negara Asia Tenggara, meski dengan arah yang berbeda. Di Thailand, partai Move Forward berhasil menarik lebih dari 45% pemilih muda dan melahirkan pemimpin berusia di bawah 40 tahun seperti Pita Limjaroenrat, bukti bahwa regenerasi bisa muncul dari politik gagasan. Di Filipina, keberadaan Sangguniang Kabataan—dewan pemuda lokal usia 15-30 tahun—menjadi laboratorium kaderisasi politik yang konkret.
Sementara itu, Malaysia, lewat kebijakan Undi 18 pada 2022, menurunkan usia pemilih dan kandidat legislatif, meningkatkan partisipasi pemuda hingga 71% pada Pemilu 2022 (SPR, 2023).

 3 hours ago
5
3 hours ago
5