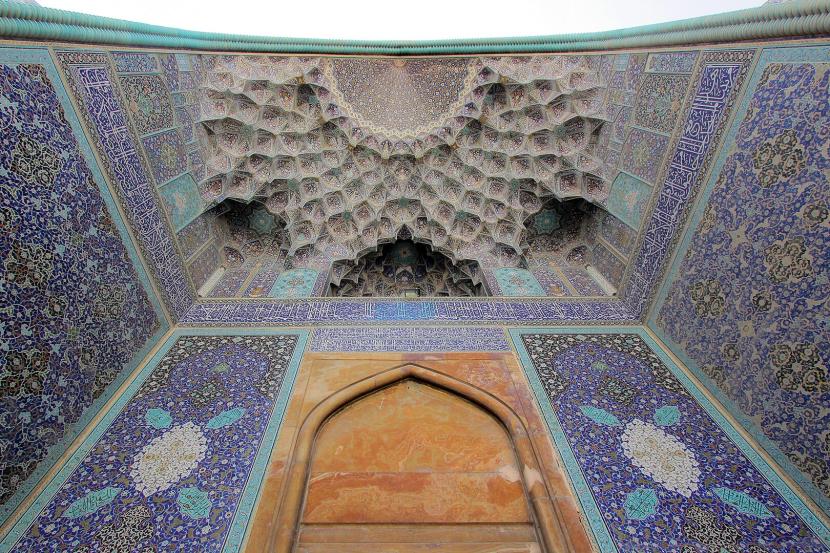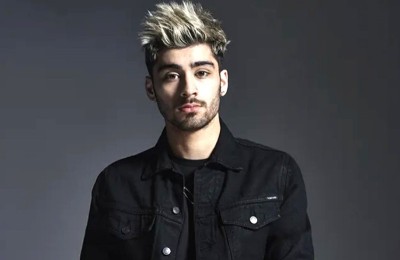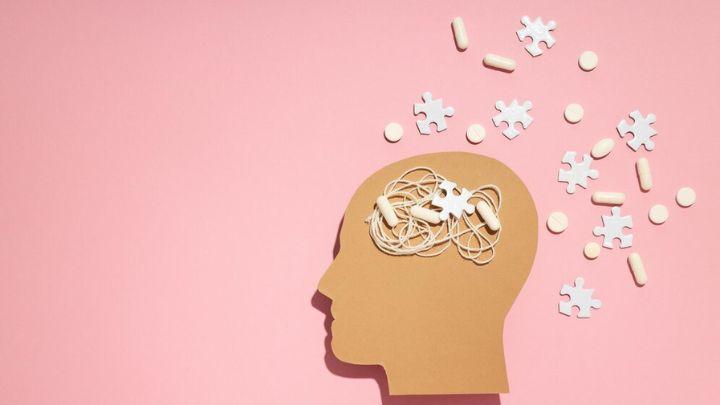syafira rachma prasetya
syafira rachma prasetya
Eduaksi | 2025-10-25 23:04:54
 Ilustrasi Suara Keras. sumber: halodoc
Ilustrasi Suara Keras. sumber: halodoc
Pernah nggak sih saat kamu lagi fokus ngerjain sesuatu tiba-tiba dengar suara petasan atau klakson keras terus tubuh langsung refleks kaget? Detak jantung meningkat “deg-degan”, bahu menegang, dan kadang tangan ikut bergetar. Hal sederhana itu nyatanya mengandung proses biologis yang rumit di dalam otak kita. Fenomena yang dimaksud dikenal dalam kajian biopsikologi sebagai “refleks sobekan”. Hal ini melibatkan respon otomatis otak kita terhadap suara keras secara mendadak yang dipersepsikan sebagai ancaman. Alih-alih sekadar “refleks kaget”, respons ini menggambarkan bagaimana sistem saraf, hormon stres, dan bagian otak tertentu bekerja bersama untuk “merawat” manusia.
Refleks startle itu kayak alarm keamanan kuno yang udah diwariskan dari zaman nenek moyang kita sejak evolusi. Ketika suara keras datang tiba-tiba, otak langsung panik, amigdala yang juga pusat emosi dan rasa takut, langsung nyalain mode darurat. Menurut Sari dan Sari (2018), amigdala itu super cepat ngerespons stimulus auditorik yang dianggap ancaman, langsung ngirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh lewat sistem saraf otonom. Semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan sebelum kita sempet mikir 'apa itu?' Suara masuk telinga, impuls langsung loncat ke batang otak, dan amigdala langsung aksi. Hasilnya, tubuh kita kayak 'freeze' sejenak, siap-siap buat lawan atau kabur.
Hartono (2017) tambahin, respons cepat ini juga ngelibatin pons dan medulla oblongata, dua bagian otak bawah yang ngatur refleks dasar. Begitu mereka aktif, jelas banget kenapa kita langsung terkejut fisik—kayak tubuh kita lagi latihan survival instan. Gila, ya, otak kita ternyata punya sistem pertahanan yang begitu canggih dan otomatis
Nggak cuma amigdala yang kerja keras, sistem endokrin juga ikut nimbrung bereaksi. Menurut Wijaya dan Setiawan (2020), suara keras bisa bikin produksi adrenalin dan kortisol (dua hormon stres utama) naik drastis. Ini terjadi karena aktivasi sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA axis), yang kayak komando pusat buat siapin tubuh hadapi ancaman. Adrenalin langsung bikin jantung deg-degan dan darah mengalir ke otot-otot besar, kayak mesin turbo yang dinyalain. Sementara kortisol jaga kewaspadaan dan energi stabil, biar kita nggak lemes pas bahaya datang. Nah, inilah kenapa kita susah tenang atau merasa telinga kayak mau pecah pas denger suara keras—tubuh kita lagi mode 'siaga satu.
Ada sesuatu yang menarik lagi yaitu jika seseorang sering mendengar suara yang keras, seperti para pekerja di area industri atau penduduk di wilayah yang banyak lalu lintas, kadar hormon stres ini bisa berefek secara kronis dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Seperti dalam penjelasan, Lestari & Prabowo (2021), yang menunjukkan bahwa paparan berkali-kali terhadap suara dan kualitas suara yang keras dapat meningkatkan risiko kecemasan, dan gangguan tidur.
Selain hormon, suara keras juga memengaruhi kerja neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengirim sinyal antar neuron di otak. GABA (gamma-aminobutyric acid) berfungsi untuk menekan aktivitas otak yang berlebihan, sedangkan glutamat justru memperkuat sinyal rangsangan saat otak menerima suara keras secara tiba-tiba (Kurniawan, 2019)
Interaksi antara dua neurotransmiter ini menjelaskan kenapa ada orang yang lebih sensitif terhadap suara keras dibanding yang lain. Misalnya, individu dengan kadar GABA yang lebih rendah cenderung mengalami reaksi kaget (startle) yang lebih kuat. Selain itu, faktor genetik juga punya peran — variasi gen yang memengaruhi sensitivitas reseptor dopamin dan serotonin bisa mengubah seberapa besar ambang seseorang dalam bereaksi terhadap suara mendadak (Kurniawan, 2019).
Dari sudut pandang biopsikologi, reaksi kita terhadap suara keras itu tidak sekadar soal loncat kaget aja, lho. Ini sebenarnya bagian dari sistem adaptif manusia yang bantu kita bertahan hidup, kayak alarm darurat di tubuh. Tapi di era sekarang, di mana kehidupan penuh suara-suara, respons ini bisa malah bikin masalah, nih.
Misalnya, Lestari dan Prabowo (2021) bilang, kalau terus-terusan diterpa suara keras, risiko stres kronis dan gangguan kecemasan bisa naik drastis. Otak kita yang selalu 'waspada' kayak ini bikin sistem saraf nggak bisa istirahat, akhirnya kita mudah lelah, tegang, atau bahkan susah tidur malam. Bayangin aja, kayak mesin yang nggak pernah dimatiin—lama-lama rusak sendiri.
Nah, paham mekanisme ini penting banget, terutama buat orang kayak pekerja pabrik, pengemudi truk, atau warga kota besar yang tiap hari dikelilingi suara bising. Mereka bisa pakai strategi pencegahan, misalnya pakai earplug atau bikin ruangan kerja lebih tenang. Dari sisi psikologi juga, kesadaran ini bantu kita sadar bahwa rasa kaget atau cemas karena suara keras itu bukan tanda lemah, tapi respon biologis alami otak yang lagi berusaha melindungi diri.
Respons otak kita terhadap suara keras yang datang tiba-tiba itu sebenarnya hasil kerja tim yang kompleks banget, gabungan dari sistem saraf, hormon, dan neurotransmiter yang tugasnya jaga keselamatan kita. Amigdala dan batang otak langsung nyalain refleks startle kayak alarm kebakaran, sementara hormon stres macam adrenalin dan kortisol bikin tubuh siap-siap buat hadapi ancaman, kayak pasang kuda-kuda buat lawan badai. Neurotransmiter seperti glutamat dan GABA juga ikut atur seberapa kuat reaksi itu, bahkan bisa dipengaruhi oleh gen kita masing-masing, kayak ada yang punya alarm lebih sensitif dari yang lain.
Fenomena ini nunjukin kalau tubuh dan otak manusia memang dirancang buat bereaksi cepat kalo ada bahaya, biar kita nggak kena musibah. Tapi di zaman sekarang, di mana suara bising jadi menu sehari-hari, reaksi ini kadang terasa overkill, deh. Nah, dengan paham mekanisme biologisnya, kita bisa lebih cerdas ngatur lingkungan sekitar, contohnya kayak kurangin kebisingan di rumah atau kerja biar bisa jaga keseimbangan antara waspada dan tenang. Jadi, nggak usah panik kalau loncat kaget, itu cuma otak kita yang lagi kerja keras lindungin diri.
Referensi
Hartono, M. (2017). Respons auditorik otak pada stimuli suara mendadak: Tinjauan biopsikologis. Majalah Ilmu Kedokteran, 10(2), 55–70.
Kurniawan, R. (2019). Refleks startle pada manusia: Peran neurotransmitter dan genetika. Jurnal Neuroscience Indonesia, 8(3), 112–129.
Lestari, S., & Prabowo, T. (2021). Mekanisme biologis respons otak terhadap suara keras: Implikasi untuk kesehatan mental. Jurnal Psikobiologi, 14(4), 201–218.
Sari, D. P., & Sari, Y. P. (2018). Respons otak terhadap stimuli suara keras: Kajian biopsikologis. Jurnal Psikologi Universitas Indonesia, 15(2), 45–62.
Wijaya, A., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh suara keras tiba-tiba pada aktivitas otak dan hormon stres. Jurnal Biologi dan Kesehatan, 12(1), 78–95.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 6 hours ago
6
6 hours ago
6