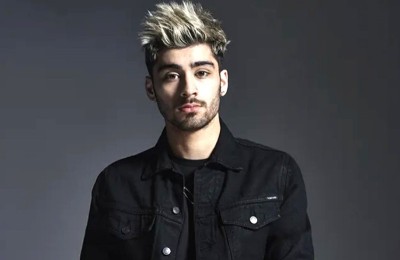Roma Kyo Kae Saniro
Roma Kyo Kae Saniro
Info Terkini | 2025-09-21 15:58:14
oleh Roma Kyo Kae Saniro
Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas
 (Ilustrasi Hantu Perempuan. Sumber: https://www.freepik.com/free-ai-image/view-scary-wet-woman_69805864.htm#fromView=search&page=1&position=41&uuid=9dc212b8-9d95-47cd-876f-c60db475bd8e&query=hantu+perempuan )
(Ilustrasi Hantu Perempuan. Sumber: https://www.freepik.com/free-ai-image/view-scary-wet-woman_69805864.htm#fromView=search&page=1&position=41&uuid=9dc212b8-9d95-47cd-876f-c60db475bd8e&query=hantu+perempuan )
“Beri rasa takut pada musuhmu dan kamu sudah memenangkan setengah dari pertempuran. Jadi Perempuan itu harus kuat. Dunia ini jahat untuk wanita. Perempuan cuman bisa disegani kalau sudah jadi hantu.” (Si Manis Jembatan Ancol, 2019).
Kutipan tersebut merupakan narasi film horor Si Manis Jembatan Ancol yang dirilis pada tanggal 26 Desember 2019. Film yang disutradarai oleh Anggy Umbara tersebut dapat dikatakan terinspirasi dari urban legend yang ada di Batavia terkait dengan Perempuan bernama Maryam yang harus terbunuh tidak jauh dari jembatan Ancol. Pada akhirnya, Maryam menjadi hantu gentayangan dan dikenal masyarakat daerah jembatan Ancol. Film Si Manis Jembatan Ancol menyajikan isu yang menari terkait dengan perempuan, hantu, dan eksistensi.
Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar tentang perempuan menurut Simone de Beauvoir. Dalam karyanya yang monumental The Second Sex (1949), Beauvoir mengemukakan gagasan bahwa “One is not born, but rather becomes, a woman” (seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan). Pernyataan ini menekankan bahwa identitas perempuan bukanlah sesuatu yang murni kodrati atau biologis, melainkan hasil konstruksi sosial, budaya, dan historis.
Beauvoir yang banyak dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre beranggapan bahwa perempuan selalu ditempatkan sebagai the Other atau second sex — makhluk kelas dua, subordinat, dan diposisikan berada di bawah laki-laki. Laki-laki selalu dipandang sebagai subjek universal, pusat pengetahuan, kekuasaan, dan penentu norma, sementara perempuan dianggap sebagai yang lain, yang identitasnya ditentukan oleh laki-laki.
Pemosisian seperti ini tentu melahirkan relasi kuasa yang timpang: ada pihak yang memegang kendali (laki-laki) dan ada pihak yang dikendalikan (perempuan). Dalam kerangka eksistensialis Beauvoir, hal ini membuat perempuan kesulitan untuk mencapai kebebasan dan otentisitas dirinya, karena mereka selalu direduksi ke dalam peran-peran tradisional yang dibentuk oleh sistem patriarki, seperti menjadi istri, ibu, atau pengurus rumah tangga.
Kondisi ini menjadikan “menjadi perempuan” sebagai sesuatu yang penuh tantangan, bahkan hingga saat ini. Meskipun banyak negara yang sudah menegakkan prinsip kesetaraan gender melalui kebijakan hukum, pendidikan, dan kesempatan kerja, kenyataannya diskriminasi dan ketidaksetaraan masih terjadi di berbagai penjuru dunia. Tidak semua negara mampu menyelaraskan kedudukan perempuan dan laki-laki secara seimbang. Bahkan, di wilayah-wilayah tertentu, perempuan masih mengalami keterbatasan hak politik, ekonomi, sosial, hingga hak atas tubuhnya sendiri.
Berfokus pada sistem patriarkal, perempuan diposisikan dirinya oleh laki-laki dengan berbagai batasan dari aspek biologis, agama, politik, budaya, dll. Keterbatasan ini membuat perempuan tidak berdaya dan tidak mampu menunjukkan eksistensinya sehingga perempuan akan tetap berada pada berbagai diskriminasi yang mengungkung dirinya. Dengan demikian, perempuan akan terus-menerus tidak berkembang dan fokus pada ranah dosmestikasi melalui sumur, kasur, dan dapur yang sebenarnya tidak ditanyakan melalui kesanggupannya terlebih dahulu.
Fenomena tersebut pun berlangsung di Indonesia walaupun tidak menyeluruh karena ada wilayah yang memeluk sistem matrilineal atau aturan berfokus pada ibu, bukan ayah seperti patriarkat. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan memotret tren kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Pada tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat peningkatan signifikan, yaitu 330.097 kasus—naik 14,17% dari tahun sebelumnya—dengan dominasi kasus di ranah personal (Komnas Perempuan, 2025). Kenaikan kasus terhadap perempuan ini menggambarkan bahwa permasalahan terkait perempuan tidak pernah selesai.
Senada dengan yang dinarasikan oleh film Si Manis Jembatan Ancol (2019), perempuan hanya dapat disegani kalau sudah menjadi hantu. Hal ini pun didukung oleh berbagai jenis hantu perempuan yang ada, seperti kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel, kuyang, suster ngesot, Badarawuhi. Dalam narasinya pun, hantu-hantu tersebut pada awalnya adalah perempuan yang mengalami diskriminasi saat hidup dan meninggal dalam keadaan tragis sehingga akhirnya dipercaya menjadi hantu. Kuntilanak yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia dijelaskan sebagai perempuan yang meninggal secara tragis saat hamil atau melahirkan sehingga rohnya gentayangan. Lalu, sundel bolong berasal dari narasi perempuan yang diperkosa dan melahirkan anaknya dalam keadaan meninggal secara tidak wajar. Wewe Gomber yang bunuh diri setelah membunuh suaminya yang berselingkuh karena wewe gombel yang dianggap tidak dapat memberikan keturunan. Oleh karena itu, ketika menjadi hantu, wewe gombel akan menculik anak-anak yang masih berkeliaran saat magrib tiba.
Suster ngesot berasal dari perempuan yang berprofesi sebagai perawat keturunan Belanda yang dibunuh secara keji, khususnya kakinya yang dipatahkan sehingga ia tidak dapat berjalan dan gentayangan. Berbeda dengan Badarawuhi yang berasal dari kerajaan pantai Selatan yang merupakan pengikut Sang Ratu yang tidak mau keluar dari tubuh Ratna Nareh dan diusir dari kerajaan. Selanjutnya, kuyang yang berasal dari perjanjian ilmu hitam yang bertujuan untuk mendapatkan keabadian atau kekuatan supranatural.
Kematian tragis yang dialami para perempuan dalam berbagai kisah rakyat maupun legenda di Indonesia sering kali dihubungkan dengan kemunculan mereka kembali dalam wujud hantu. Sosok-sosok seperti sundel bolong, kuntilanak, atau nyai roro kidul menjadi representasi bagaimana perempuan yang semasa hidupnya tertindas atau mengalami penderitaan justru memperoleh kekuatan setelah kematian. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan kepercayaan terhadap takhayul, keberadaan roh gentayangan ini tidak sekadar menakutkan, melainkan juga memperlihatkan bentuk lain dari eksistensi perempuan yang selama hidupnya kerap dipinggirkan.
Pada titik ini, muncul ironi yang menarik berupa ketika masih hidup, perempuan kerap dianggap lemah, tidak berdaya, bahkan diposisikan sebagai “kelas dua” di bawah laki-laki. Namun, setelah mati dengan cara tragis, mereka justru berubah menjadi sosok yang ditakuti oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, kepercayaan terhadap hantu perempuan dalam kebudayaan Indonesia secara tidak langsung menghadirkan pengakuan atas eksistensi perempuan — meskipun pengakuan tersebut lahir dalam bentuk yang seram, menakutkan, dan penuh balas dendam.
Namun demikian, dalam kerangka eksistensialisme ala Beauvoir, kematian tetaplah akhir dari proses kehidupan sebagai manusia. Ketika perempuan hanya diakui setelah menjadi makhluk lain (hantu, roh gentayangan, atau simbol mistis), hal ini menunjukkan bahwa eksistensi perempuan sebagai manusia hidup masih terpinggirkan. Perempuan tidak mendapatkan pengakuan sejati atas keberadaannya di dunia nyata, melainkan baru dihormati atau ditakuti ketika mereka keluar dari kemanusiaannya dan memasuki ranah supranatural.
Lebih jauh, situasi ini mencerminkan relasi antara gender, budaya patriarki, dan kepercayaan tradisional di Indonesia. Masyarakat yang sangat mempercayai takhayul memproduksi narasi bahwa “kekuatan” perempuan baru hadir setelah ia tidak lagi hidup. Hal ini menegaskan bahwa dalam konstruksi budaya, perempuan kerap diposisikan ambigu: di satu sisi dipandang lemah dan tidak berdaya, namun di sisi lain juga dipandang berbahaya dan menakutkan. Ambiguitas inilah yang membuat figur hantu perempuan dalam budaya populer Indonesia begitu dominan dan terus hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat.
Fenomena “perempuan yang hanya disegani setelah menjadi hantu” menyingkap ironi dalam konstruksi budaya patriarki Indonesia. Saat hidup, perempuan kerap dipinggirkan, dilemahkan, dan direndahkan, namun setelah mati secara tragis, mereka justru menjelma menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati. Kisah-kisah kuntilanak, sundel bolong, atau suster ngesot bukan sekadar cerita horor, melainkan cermin dari realitas sosial: perempuan sering kali baru memperoleh pengakuan eksistensinya ketika ia tak lagi menjadi manusia seutuhnya. Dalam kerangka pemikiran Simone de Beauvoir, situasi ini memperlihatkan betapa sulitnya perempuan untuk diakui sebagai subjek bebas dalam kehidupan nyata. Namun, hadirnya figur hantu perempuan dalam imajinasi kolektif masyarakat juga membuka ruang kritik terhadap tatanan sosial yang menindas. Hantu-hantu itu menjadi simbol perlawanan—suara bisu perempuan yang ditindas, sekaligus peringatan bahwa menekan eksistensi perempuan hanya akan melahirkan kekuatan lain yang lebih menakutkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 2 months ago
27
2 months ago
27