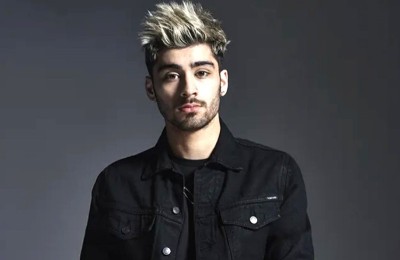Oleh : M Luthfi Hamidi; Editor in-Chief Muslim Business and Economics Review, Dosen FEB UIII
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akhir bulan ini, tepatnya tanggal 29-31 Oktober 2025, bertempat di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), akan digelar hajatan konferensi internasional unggulan dari Kementrian Agama. Konferensi dimaksud adalah Annual International Conference on Islamic Studies Plus (AICIS+) yang sudah diselenggarakan sejak dua dekade lalu.
Yang menarik dari even ini ada penambahan “plus” (+) yang menyiratkan spirit dan muatan baru yang hendak dikenalkan, antara lain adanya kegiatan tambahan (Side event) yang mencakup Pemeran Pendidikan dan Iptek (dengan titik tumpu kontribusi madrasah), Pameran buku dan launching buku, dan pameran halal dan kuliner internasional. Yang tidak kalah menarik adalah kegiatan inti konferensi itu sendiri yang kali ini akan diikuti peserta dari 21 negara dari lima benua (Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika).
Total 204 artikel yang diterima panitia, di antaranya 61 paper membahas ekoteologi dan sustainabilitas lingkungan (Ecological theology and Environmental sustainability) dan 27 peserta lainnya membahas sistem ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (sustainable economic system and social welfare). Sisanya membahas dekolonisasi Islam (32), hukum Islam dan ekofeminisme (31), peacebuilding dan krisis kemanusiaan (32), sisanya membahas isu di seputar kesehatan, inovasi dan teknologi. Dengan kata lain, 43 persen dari artikel memiliki cakupan bidang ekoteologi dan sustainability.
Ekoteologi
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam berbagai kesempatan mengeksplorasi kajian Ekoteologi. Kajian ini meneliti relasi antara agama dan lingkungan, lebih praktisnya bagaimana konsep agama yang terkait lingkungan (teologi) bisa diimplementasikan untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup. Bahkan, di tingkat kebijakan, kajian Ekoteologi masuk dalam agenda prioritas Kementerian agama (2025-2029), tertuang dalam KMA Nomor 244 tahun 2025. Kebijakan ini memberikan arahan bahwa ASN di bawah Departemen Agama didorong untuk menjadi pioner dalam implementasi ekoteologi baik dalam bentuk program kebijakan maupun kegiatan riil sehari-hari.
Kajian Ekoteologi sebetulnya bukan hal baru. Lynn White Jr. (1967 melalui artikelnya "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" dinisbatkan sebagai ahli yang mulai menggelorakan kajian tema ini. Ia mengkritik pandangan antroposentris dalam tradisi Kristen yang menafsirkan dominion (kekuasaan) manusia atas alam sebagai lisensi untuk eksploitasi. Kritiknya ini mendorong para teolog untuk merefleksikan kembali ajaran agama mereka. Disusul kemudian Sallie McFague (1993) yang menulis The Body of God: An Ecological Theology, di mana dunia digambarkan sebagai Tubuh Allah (The Body of God)— pengunaan dan eksplorasi sembarangan atas dunia adalah cerminan absennya tanggung jawab etis dan ekologis manusia.
Jauh sebelum White dan McFague, Imam al-Ghazali dalam kitabnya Mīzān al-‘Amal menyebutkan alam besertanya isinya adalah bentuk ”tatan ciptaan-Nya” (niẓām ṣun‘ihi) yang mengisyaratkan keteraturan (order) alam raya yang merupakan cerminan dari kebijakan Tuhan. Karena itu bumi dan alam raya harus dimakmurkan dan dijaga dan bukan sebaliknya dirusak. Inilah yang kemudian menjadi dasar dan menginspirasi Seyyed Hossein Nasr (1968) untuk membangun teologi lingkungan Islam yang kemudian ia bukukan dalam Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man.
Sustainability
Ekoteologi boleh dibilang cabang kajian dari Sustainability. Kalau Ekoteologi lebih konsen kepada lingkungan (planet), Sustainability tidak hanya ini, tapi membahas dua aspek yang lain, yaitu aspek keuangan (profit) dan aspek sosial kemasyarakatan (people). Menurut Milton Friedman, peraih Nobel Ekonomi (1976), tugas utama bisnis adalah meningkatkan profit. Namun, pendapat ini belakangan mendapatkan kritikan tajam karena bisnis tidak hanya menciptakan keuntungan, tapi juga efek sampingan (externalities) seperti halnya polusi dan kerusakan alam sebagai dampak eksploitasi berlebihan. Dari sinilah, Elkington (1997) merekomendasikan entitas bisnis seharusnya menyatukan tiga hal (profit, people, planet) dalam sebuah framework yang dikenal sebagai triple bottom line (TBL). Konsep TBL ini kemudian mendapatkan pengakuan yang luas dan aplikasinya dalam dunia perusahaan.
Dalam perspektif Islam, Sustainability juga bukan hal yang baru. Bahkan ada peristiwa unik digambarkan dalam al-Quran yang memberikan gambaran keberlanjutan hanya dalam satu ayat saja (Surat al-Qasshos: 77). ”Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.” Ayat ini menceritakan bagaimana Qorun bilyuner saat itu karena kesombongannya semua keluarga, kekayaan, kaki tangannya, ditelan bumi. Dengan tidak lain tidak berkelanjutan.
Frase ” janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia” dalam ayat itu cerminan setiap kegiatan usaha harus profesional (profit), sedang ” Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu” menunjukkan bisnis tidak bisa terpisah dari masyarakatnya (people), dan pesan terakhir ” dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi” adalah pesan yang eksplisit untuk menjaga dan melestarikan alam (planet).
Hamidi dan Worthington (2021) menambahkan 3P (profit, people, planet) Elkington dengan satu tambahan yang diinspirasikan dari ayat tersebut yang diawali dengan frase ”carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat”. Untuk mendapatkan pahala akhirat, seseorang harus meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Implementasi 3P harus diinspirasi dari nilai-nilai kenabian (Prophetic). Diselaraskan dengan pesan ini, jadilah TBL kemudian diselaraskan menjadi 4P atau Quadruple Bottom Line (QBL). Dengan melihat ini, rumusan Ekoteologi sudah menjadi bahasan dalam framework baru (QBL). Dalam framework ini, semua nilai-nilainya didasarkan tujuan asasi dari hukum Islam (Maqasid al-Syari’ah) dengan memasukkan unsur lingkungan (fiqh al-bi’ah) yang digagas oleh An-Najjar (2006).
Kontribusi
Berdasarkan laporan dari Forest Declaration Assessment (2023), Indonesia menduduki peringkat ke-2 di dunia untuk luas deforestasi (pembabatan hutan) dengan angka sekitar 1,18 juta ha, di belakang Brasil (1,94 juta ha). Statistik yang sangat menyedihkan dan karenanya inisiatif Menteri Agama mendorong bagi implementasi ekoteologi menjadi penting. Saat memperingat Hari Bumi, April lalu, Kementrian Agama menginstruksikan penanaman sejuta pohon di seluruh kantor di Indonesia. Kontribusi ini mungkin juga dilakukan kementrian lain.
Namun ada kebijakan yang perlu menjadi prioritas dan sangat relevan dengan Ekoteologi yang sisi regulasinya ada di Kementrian Agama: Mengatur keberlanjutan masjid. Masjid menjadi penting karena rumah ibadah ini menjadi pusat kegiatan umat Islam. Kalau praktik keberlanjutan digalakkan di masjid, bukan hanya masjidnya yang bisa sustainable, tapi juga perilaku jamaahnya.
Statistik masjid dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, per 20 Oktober 2025, ada 315.990 masjid dan 388.177 musholla atau total 704.167. Menurut perkiraan jumlah masjid di dunia mencapai 3,6 juta lebih (2021) yang berarti masjid di Indonesia mencapai hampir 20 persen dari jumlah masjid di dunia. Penelitain yang dilakukan Hamidi, Setiawan, dan Asutay (2025) yang dipublikasikan di jurnal Sustainable Futures dengan mengambil sampel 97 masjid di DKI Jakarta dan menggunakan pengukuran prinsip 4P (QBL) mengungkap 68 masjid sudah pada level sustainable, sisanya (32 persen) belum. Kalau di Jakarta saja masih ada sepertiga kasus masjid yang belum sustainable, bagaimana dengan masjid-masjid di daerah? Kalau masalah ini bisa ditangani, tentu akan menjadi salah satu titik kontribusi aktif Indonesia terkait Ekoteologi untuk dunia.

 3 hours ago
4
3 hours ago
4