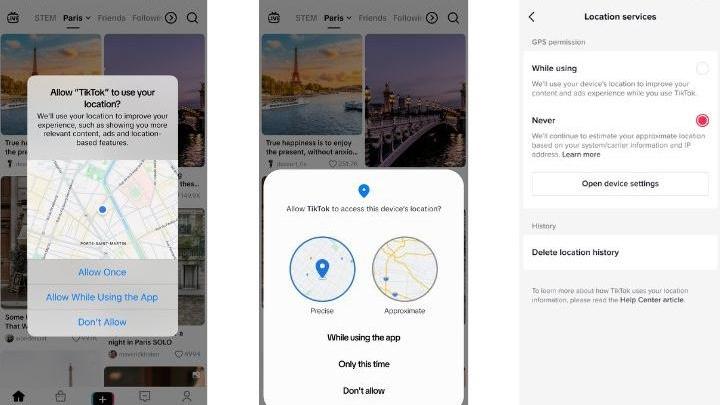Oleh : Prof Suwatno; Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah optimisme demografis yang selama ini diagungkan pemerintah, ada bunyi retak yang makin keras terdengar: retaknya masa depan Generasi Z di pasar kerja Indonesia. Data LPEM FEB UI baru-baru ini menunjukkan fakta mencemaskan: 45 ribu lulusan S1 putus asa mencari kerja (Detik, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi alarm keras tentang generasi yang kehilangan pegangan sebelum benar-benar memasuki dunia dewasa.
Fenomena Gen Z yang tidak bekerja tetapi juga tidak lagi mencari kerja berkelindan dengan realitas yang lebih luas: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berada pada kelompok usia 15–24 tahun, mencapai 16,16 persen. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran Indonesia hari ini adalah bagian dari generasi yang disebut paling terdidik, paling digital, dan paling adaptif. Ironisnya, justru mereka yang paling terlempar dari arena kompetisi.
Selain itu, banyak Gen Z yang menunda atau berhenti mencari kerja karena tidak tahu keterampilan apa yang sebenarnya mereka kuasai. Ada kebingungan orientasi: lulusan merasa kompetensinya tidak sesuai kebutuhan industri, sementara industri bergerak begitu cepat. Sebagian bahkan merasa “terlalu tua” untuk posisi entry-level, atau merasa upah yang ditawarkan jauh dari ekspektasi realistis hidup perkotaan saat ini. Kombinasi ini menciptakan situasi yang disebut skill-mismatch, alias keterputusan antara apa yang diajarkan pendidikan dan apa yang dibutuhkan pasar kerja.
Di sinilah tampak jelas bahwa persoalan pengangguran Gen Z bukan sekadar masalah “kurang usaha”, melainkan masalah struktural. Sistem pendidikan Indonesia masih didominasi hafalan, jenjang linier, dan penekanan pada gelar. Ketika mereka keluar ke dunia kerja, yang dituntut justru adalah fleksibilitas, portofolio proyek, kecerdasan digital, dan kemampuan problem-solving.
Bryan Caplan (2018) dalam The Case Against Education menyebut fenomena yang kini dihadapi pasar tenaga kerja sebagai “inflasi kredensial,” yakni situasi ketika gelar akademik tidak lagi berfungsi sebagai penanda kecakapan, melainkan sekadar tiket masuk paling dasar untuk dipertimbangkan dalam proses rekrutmen.
Ketika semakin banyak orang memiliki ijazah yang sama, nilai pembeda dari gelar tersebut menurun drastis. Akibatnya, dunia kerja menuntut indikator kompetensi baru yang lebih konkret: portofolio, pengalaman, kemampuan problem-solving, serta kecakapan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, ijazah berubah dari simbol prestasi menjadi sekadar “sinyal” bahwa seseorang mampu menyelesaikan pendidikan formal, bukan jaminan bahwa ia menguasai keterampilan yang dibutuhkan.
Gen Z Indonesia memasuki pasar kerja tepat pada puncak inflasi kredensial ini, ketika persaingan tidak hanya semakin ketat, tetapi juga semakin tidak seimbang. Mereka berhadapan dengan realitas bahwa gelar sarjana tidak lagi cukup untuk membuka pintu kesempatan, sementara perguruan tinggi belum sepenuhnya menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri yang kian bergerak cepat.
Pada saat bersamaan, transformasi teknologi memperparah keadaan. Martin Ford (2015) dalam The Rise of the Robots mengingatkan bahwa jutaan pekerjaan manusia tertelan automasi dan kecerdasan buatan. Bukan hanya pekerjaan manufaktur, tetapi pekerjaan administratif, perbankan, bahkan penulisan laporan.
Di Indonesia, gejalanya tampak pada banyak perusahaan yang semakin mengutamakan efisiensi digital, dan menilai pekerja muda “belum siap beradaptasi secara teknis”. Ketika kebutuhan kompetensi berubah dalam hitungan bulan, lulusan baru yang tidak mendapatkan pendampingan transisi otomatis tertinggal.
Namun persoalan Gen Z tidak berhenti pada sisi teknis. Ada dimensi psikologis dan sosial yang sering diabaikan. David Graeber (2018) dalam Bullshit Jobs menyebut banyak pekerjaan modern sebagai “pekerjaan tanpa makna”, yakni pekerjaan yang tidak memberi kontribusi jelas dan tidak memberikan kepuasan psikologis. Sebagian Gen Z menolak pekerjaan yang dinilai eksploitatif, tidak layak, atau tidak manusiawi. Penolakan ini sering dibaca sebagai “manja”, padahal lebih tepat dibaca sebagai kesadaran baru tentang martabat dan nilai diri.
Sosiolog Ronaldo Munck (2018) dalam Rethinking Global Labour: After Neoliberalism menggambarkan munculnya kelas baru pekerja muda global yang hidup dalam kondisi rentan. Indikatornya antara lain pekerjaan tidak stabil, upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan selalu berada di bawah ancaman PHK. Inilah yang kini dialami banyak Gen Z di Indonesia. Mereka tidak sekadar menganggur; mereka terjebak dalam struktur ekonomi yang tidak memberi mereka pijakan.
Fenomena pengangguran Gen Z harus dibaca sebagai sinyal kegagalan kolektif. Kita sedang menyaksikan runtuhnya kontrak sosial antara pendidikan, negara, dan dunia kerja. Pendidikan menjanjikan jalan menuju masa depan; negara menjanjikan peluang; industri menjanjikan karier. Tetapi janji itu kini retak di tangan kenyataan.
Solusi
Pertama, sistem pendidikan tinggi harus berani merevisi kurikulum, dari fokus pada teori menuju experiential learning yang relevan dengan industri. Mahasiswa harus memiliki portofolio, bukan sekadar transkrip nilai.
Kedua, pemerintah perlu membangun sistem informasi pasar kerja yang akurat dan dinamis. Lulusan harus tahu keterampilan apa yang sedang naik daun, industri mana yang sedang tumbuh, dan bagaimana mereka dapat melakukan reskilling secara terjangkau.
Ketiga, perusahaan perlu mengubah cara mereka melihat Gen Z. Alih-alih menuntut kesiapan penuh sejak hari pertama, perusahaan seharusnya menyediakan onboarding dan pelatihan awal yang memadai, sebab generasi muda adalah investasi jangka panjang.
Keempat, kita perlu membangun narasi baru tentang pekerjaan—bahwa karier tidak selalu linier, bahwa keterampilan dapat dipelajari sepanjang hidup, dan bahwa gagal pada usia muda adalah normal. Harapan harus dipulihkan.
Generasi Z sejatinya bukan generasi lemah. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah perubahan paling cepat dalam sejarah manusia. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan. Sebaliknya, mereka membutuhkan struktur sosial yang adil, pendidikan yang relevan, dan pasar kerja yang manusiawi. Jika kita gagal membenahi ini sekarang, maka “bonus demografi” yang dibanggakan itu bisa berubah menjadi beban sejarah.
Indonesia tidak kekurangan talenta muda. Yang kurang adalah jembatan yang memadai untuk membawa mereka masuk ke dunia kerja. Dan jembatan itu harus mulai dibangun hari ini.

 5 hours ago
4
5 hours ago
4